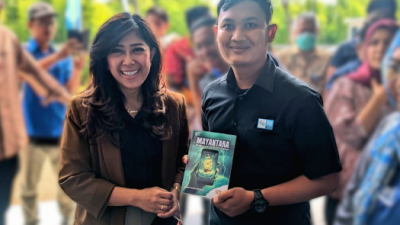Oleh : M. Ali Ghozi
Dua peristiwa besar tengah menjadi sorotan publik Indonesia tahun ini: skandal korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina dan peluncuran Dana Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga investasi strategis nasional.
Di satu sisi, publik dikecewakan oleh penyalahgunaan kekuasaan di tubuh BUMN energi. Di sisi lain, ada optimisme akan kebangkitan ekonomi lewat pengelolaan investasi berskala raksasa. Namun di balik semua itu, muncul satu benang merah yang tak boleh diabaikan: dilema moral dalam tata kelola negara.
Skandal Pertamina: Ujian Etika dalam Kekuasaan Kasus dugaan korupsi di Pertamina diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun.
Berdasarkan temuan Kejaksaan Agung, sejumlah pelanggaran dilakukan dalam proses impor minyak mentah, mulai dari pengabaian prinsip tata kelola hingga dugaan mark-up harga. Skandal korupsi di tubuh Pertamina bukan sekadar pelanggaran hukum—ia adalah pengkhianatan terhadap etika publik.
Dengan estimasi kerugian negara yang sangat besar, kasus ini mencerminkan kerusakan sistemik dalam tata kelola salah satu BUMN paling strategis di negeri ini.
Namun yang mencemaskan bukan hanya nilai kerugiannya, melainkan bagaimana praktik semacam ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun di tengah jargon reformasi dan efisiensi.
Dalam situasi ketika pemerintah menggaungkan efisiensi anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, kebocoran sebesar ini justru menjadi ironi pahit. Negara bersusah payah menghemat Rp306 triliun, tapi di sisi lain, tata kelola yang rapuh menguapkan triliunan rupiah dari kekayaan rakyat.
Kasus Pertamina harus menjadi momentum koreksi menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga etika. Karena di negara yang sehat, kepercayaan publik tak boleh diperdagangkan demi keuntungan segelintir elite.