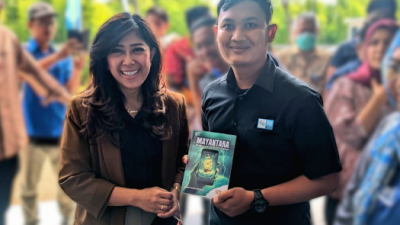Bermain merupakan kebutuhan mendasar anak dalam memahami dunia. Jean Piaget, psikolog perkembangan ternama, menyebut bermain sebagai wahana utama anak membangun struktur kognitifnya. Melalui permainan, anak tidak hanya bersenang-senang, melainkan juga belajar mengamati, meniru, memecahkan masalah, dan mengembangkan logika.
Lev Vygotsky melangkah lebih jauh. Ia mengemukakan bahwa bermain menempatkan anak dalam “zona perkembangan proksimal”—wilayah di mana anak mampu mencapai keterampilan baru melalui interaksi sosial dan bimbingan teman sebaya. Dalam permainan seperti gobak sodor, petak umpet, atau engklek, anak belajar negosiasi, kerja sama, serta memahami aturan sosial yang kompleks.
Namun, di era digital ini, permainan tradisional perlahan bergeser. Anak-anak kini lebih akrab dengan layar gadget ketimbang lapangan terbuka. Transformasi ini tak sepenuhnya keliru. Teknologi, jika digunakan secara tepat, bisa menjadi sarana pendidikan yang luar biasa. Sherry Turkle, profesor MIT, dalam bukunya Alone Together (2011) menyebut bahwa teknologi digital memperluas kesempatan belajar, namun juga membawa risiko “isolasi sosial dalam keterhubungan semu.”
Anak-anak yang terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan cenderung mengalami penurunan kemampuan interaksi nyata. Dr. Dimitri Christakis, direktur Center for Child Health, Behavior, and Development di University of Washington, menemukan bahwa penggunaan media digital berlebihan pada usia dini berkorelasi dengan gangguan atensi, keterlambatan bicara, serta penurunan keterampilan sosial.
Di sisi lain, bermain fisik tetap menjadi kebutuhan biologis anak. Dr. Stuart Brown, pendiri National Institute for Play, menyatakan bahwa permainan aktif “merangsang otak anak untuk berkembang lebih adaptif, kreatif, dan resilien.” Ia menegaskan bahwa anak yang kekurangan aktivitas bermain fisik cenderung tumbuh dengan kapasitas sosial dan emosional yang lebih rapuh.