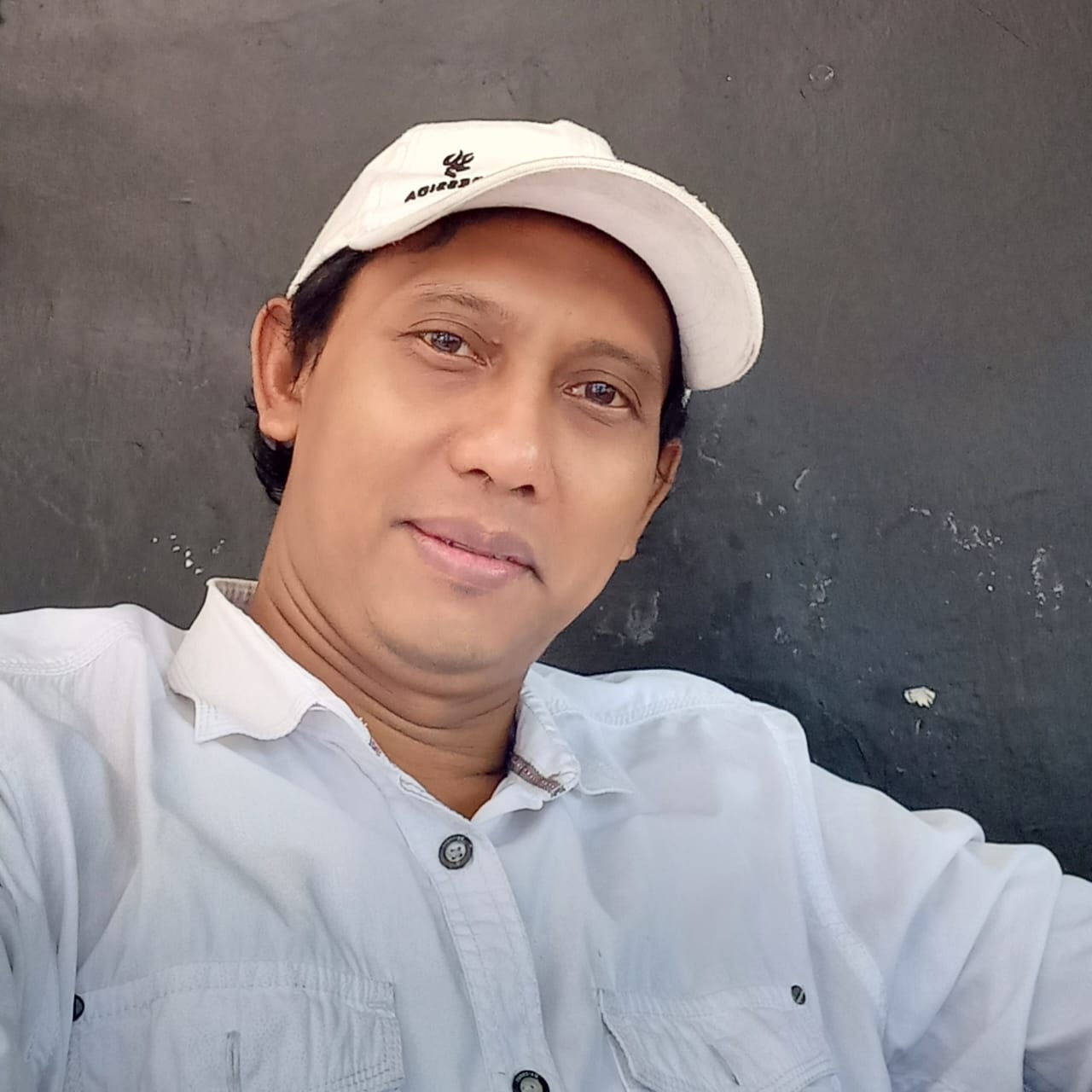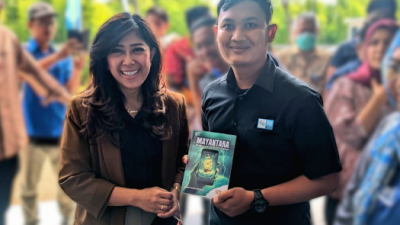KECAMATAN Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kembali dilanda bencana tanah longsor pada awal tahun 2025. Desa-desa seperti Mendala, Manggis, Sridadi, dan Mlayang menjadi saksi betapa rentannya bentang alam kawasan ini ketika alam mulai bicara. Longsor yang terjadi di berbagai titik, mulai dari Dusun Krajan di Mendala hingga wilayah Jatiteken dan Siroyom di Desa Mlayang, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar fenomena musiman akibat curah hujan tinggi. Ini adalah hasil akumulasi dari praktik eksploitasi dan abainya manusia terhadap ekosistem.
Sirampog dan Warisan Alamnya.
Sirampog terletak di kaki selatan Gunung Slamet, kawasan yang sejak lama dikenal dengan kesuburan tanahnya dan keberlimpahan air dari mata air pegunungan. Sawah terasering, kebun hortikultura, dan hutan rakyat dulunya menjadi ciri khas dari kecamatan ini. Namun, dalam dua dekade terakhir, wajah alam Sirampog berubah drastis.
Hutan-hutan yang dulu rimbun, kini sebagian besar telah berubah menjadi kebun sayur intensif. Mata air yang dulu mengaliri sawah kini menyusut, bahkan menghilang. Banyak lahan yang dulu subur berubah menjadi lahan kritis. Masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tanpa disadari telah meminjam terlalu banyak dari alam, tanpa pernah membayar kembali.
Kronologi dan Sebaran Longsor
Longsor di Kecamatan Sirampog pada awal 2025 bukan hanya satu peristiwa tunggal. Ini adalah rangkaian bencana di berbagai desa:
• Desa Mendala: Terjadi di Dusun Krajan, memutus akses jalan desa, merusak sejumlah rumah, dan mengancam lahan pertanian.
• Desa Manggis: Longsor besar di Dukuh Sambungregel menimbun ruas jalan penghubung dan menyebabkan trauma mendalam pada warga.